Musik Keroncong
>>>>Kategori Seni Budaya<<<<
Akar keroncong berasal
dari sejenis musik Portugis yang dikenal sebagai fado yang diperkenalkan oleh
para pelaut dan budak kapal niaga bangsa itu sejak abad ke-16 ke Nusantara.
Seperti
diketahui bahwa Musik
Keroncong masuk ke Indonesia sekitar tahun 1512, yaitu pada waktu Ekspedisi
Portugis pimpinan Alfonso de Albuquerque datang ke Malaka dan Maluku tahun
1512. Tentu saja para pelaut Portugis membawa lagu jenis Fado, yaitu
lagu rakyat Portugis bernada Arab (tangga nada minor, karena orang Moor Arab
pernah menjajah Portugis/Spanyol tahun 711 - 1492. Lagu jenis Fado masih ada di
Amerika Latin (bekas jajahan Spanyol), seperti yang dinyanyikan Trio Los
Panchos atau Los Paraguayos, atau juga lagu di Sumatera Barat (budaya Arab)
seperti Ayam Den Lapeh.
Dalam
bentuknya yang paling awal, moresco diiringi oleh musik dawai, seperti biola,
ukulele, serta selo. Perkusi juga kadang-kadang dipakai. Set orkes semacam ini
masih dipakai oleh keroncong Tugu, bentuk keroncong yang masih dimainkan oleh
komunitas keturunan budak Portugis dari Ambon yang tinggal di Kampung Tugu,
Jakarta Utara, yang kemudian berkembang ke arah selatan di Kemayoran dan Gambir
oleh orang Betawi berbaur dengan musik Tanjidor (tahun 1880-1920). Tahun
1920-1960 pusat perkembangan pindah ke Solo, dan beradaptasi dengan irama yang
lebih lambat sesuai sifat orang Jawa.
Pem-"pribumi"-an
keroncong menjadikannya seni campuran, dengan alat-alat musik seperti
sitar
India
rebab
suling
bambu
gendang,
kenong, dan saron sebagai satu set gamelan
gong.
Saat
ini, alat musik yang dipakai dalam orkes keroncong mencakup
ukulele
cuk, berdawai 3 (nilon), urutan nadanya adalah G, B dan E; sebagai alat musik
utama yang menyuarakan crong - crong sehingga disebut keroncong (ditemukan
tahun 1879 di Hawai, dan merupakan awal tonggak mulainya musik keroncong)
ukulele
cak, berdawai 4 (baja), urutan nadanya A, D, Fis, dan B. Jadi ketika alat musik
lainnya memainkan tangga nada C, cak bermain pada tangga nada F (dikenal dengan
sebutan in F);
gitar
akustik sebagai gitar melodi, dimainkan dengan gaya kontrapuntis (anti melodi);
biola
(menggantikan Rebab); sejak dibuat oleh Amati atau Stradivarius dari Cremona
Itali sekitar tahun 1600 tidak pernah berubah modelnya hingga sekarang;
flute
(mengantikan Suling Bambu), pada Era Tempo Doeloe memakai Suling Albert (suling
kayu hitam dengan lubang dan klep, suara agak patah-patah, contoh orkes Lief
Java), sedangkan pada Era Keroncong Abadi telah memakai Suling Bohm (suling
metal semua dengan klep, suara lebih halus dengan ornamen nada yang indah,
contoh flutis Sunarno dari Solo atau Beny Waluyo dari Jakarta);
Musiq
Losquin Bugis: Dari periode tempo doeloe ini lahir pula di Makassar bentuk
keroncong khas yang dikenal sebagai musiq losquin Bugis, misalnya lagu Ongkona
Arumpone yang dinyanyikan oleh Sukaenah B. Salamaki. Irama keroncong ini, tanpa
seruling-biola-cello, tapi dengan melodi guitar yang kental, mirip seperti gaya
Tjoh de Fretes dari Ambon. Kalau kita hubungkan kesemua ini, maka ada garis
kesamaan dengan Orkes Keroncong Cafrino Tugu (Kr. Pasar Gambir) – Orkes
Keroncong Lief Java (Kr. Kali Brantas) – Losquin Bugis (Ongkona Arumpone) –
Orkes Hawaian Tjoh de Fretes (Pulau Ambon), yaitu gaya era tempo doeloe dengan
irama yang cepat sudah dengan kendangan cello dan dengan guitar melodi yang
kental.
Musik
keroncong lebih condong pada progresi akord dan jenis alat yang digunakan.
Sejak pertengahan abad ke-20 telah dikenal paling tidak tiga macam keroncong,
yang dapat dikenali dari pola progresi akordnya. Bagi pemusik yang sudah
memahami alurnya, mengiringi lagu-lagu keroncong sebenarnya tidaklah susah,
sebab cukup menyesuaikan pola yang berlaku. Pengembangan dilakukan dengan
menjaga konsistensi pola tersebut. Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk
campuran serta adaptasi.
Tokoh
keroncong
Salah
satu tokoh Indonesia yang memiliki kontribusi cukup besar dalam membesarkan
musik keroncong adalah bapak Gesang. Lelaki asal kota Surakarta (Solo) ini
bahkan mendapatkan santunan setiap tahun dari pemerintah Jepang karena berhasil
memperkenalkan musik keroncong di sana. Salah satu lagunya yang paling terkenal
adalah(lagu)|Bengawan Solo. Lantaran pengabdiannya itulah, oleh Gesang dijuluki
"Buaya Keroncong" oleh insan keroncong Indonesia, sebutan untuk pakar
musik keroncong. Gesang menyebut irama keroncong pada MASA STAMBUL (1880-1920),
yang berkembang di Jakarta (Tugu , Kemayoran, dan Gambir) sebagai Keroncong
Cepat; sedangkan setelah pusat perkembangan pindah ke Solo (MASA KERONCONG
ABADI: 1920-1960) iramanya menjadi lebih lambat.
Asal
muasal sebutan "Buaya Keroncong" untuk Gesang berkisar pada lagu
ciptaannya, "Bengawan Solo". Bengawan Solo adalah nama sungai yang
berada di wilayah Surakarta. Seperti diketahui, buaya memiliki habitat di rawa
dan sungai. Reptil terbesar itu di habitanya nyaris tak terkalahkan, karena
menjadi pemangsa yang ganas. Pengandaian semacam itulah yang mendasari mengapa
Gesang disebut sebagai "Buaya Keroncong".
Di
sisi lain nama Anjar Any (Solo, pencipta Langgam Jawa lebih dari 2000 lagu yang
meninggal tahun 2008) juga mempunyai andil dalam keroncong untuk Langgam Jawa
beserta Waljinah (Solo), sedangkan R. Pirngadie (Jakarta) untuk Keroncong Beat,
Manthous (Gunung Kidul, Yogyakarta) untuk Campursari dan Koe Plus
(Solo/Jakarta) untuk Keroncong Rock, serta Didi Kempot (Ngawi) untuk Congdut.


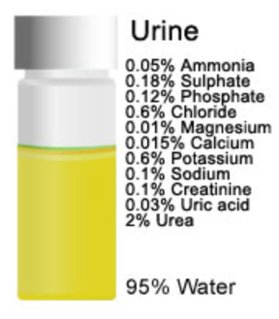
Komentar
Posting Komentar